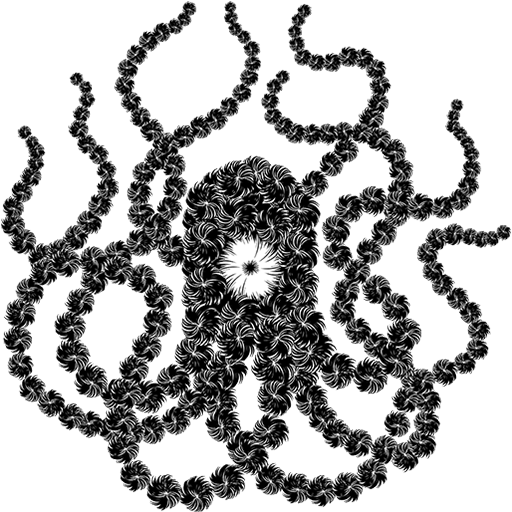‘Modular Monster’ Mulyana The Mogus Meriahkan ICAD 2019
February 19, 2020
Laki-laki dengan Jarum Rajut dan Pesona Benang
February 19, 2020Karya seni yang baik pada dasarnya selalu berusaha melawan klise.
Dunia seni dan sastra kita selama 2018 boleh dibilang masih banyak yang jatuh ke pengulangan dan pendekatan yang stereotipe. Tapi, dari sekian itu, ada seniman yang mampu mengolah tema umum dengan cara berbeda dan matang sehingga melahirkan karya yang lain. Dari dunia seni rupa, muncul karya yang bertolak dari keterampilan home craft yang biasa dikerjakan ibu-ibu di rumah (yang sering dianggap sepele oleh seni modern) menjadi karya kontemporer unik.
Dari khazanah novel, muncul teks yang menggunakan idiom dunia wayang tapi lebih mengambil strategi penceritaan seperti bayang-bayang wayang sendiri, bergerak di antara prosa dan puisi, di antara yang nyata dan yang maya. Dari khazanah persajakan, muncul sebuah kumpulan puisi yang berangkat dari pengembaraan akan hal-ihwal sebuah kota asing tapi tak sekadar menyajikan impresi-impresi seorang pelancong sebagaimana banyak ditunjukkan penyair umumnya.
Dan, dari seni pertunjukan, tampil sebuah karya yang sederhana, menghindari keriuhan gerak sebagaimana kini banyak didemonstrasikan koreografer kita, tapi mampu memberikan sugesti serta asosiasi antara kata, gerak, dan bunyi yang membekas. Dari dunia industri rekaman, muncul sebuah kelompok musik yang mengeksplorasi dunia folklore tanpa ingin terjatuh pada eksotisme. Pada tiap awal tahun, Tempo selalu memilih karya-karya seni tahun sebelumnya yang dianggap memikat. Inilah karya dan tokoh seni pilihan Tempo sepanjang 2018.
Dengan tinggi 121 meter dan lebar 64 meter, patung raksasa Garuda Wisnu Kencana berdiri menjulang di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang luasnya sekitar 60 hektare. Boleh dibilang patung gigantik seberat 3.000 ton rancangan perupa I Nyoman Nuarta itu merupakan patung publik paling monumental selama 2018. Selain ukurannya sangat besar, proses pengerjaannya menelan waktu yang sangat lama: 28 tahun.
Pembaca, seperti tahun-tahun lalu, pada awal Januari ini kami berusaha menengok perkembangan dunia seni dan sastra tahun sebelumnya. Kami memilih karya-karya seni dan sastra yang kami anggap inovatif, menyegarkan, mampu menyajikan kedalaman, serta membuka kemungkinan-kemungkinan artistik baru. Untuk penjurian seni, sastra, dan musik pilihan Tempo 2018 ini, kami mengundang pengamat sastra dan penulis Seno Gumira Ajidarma, kritikus sastra Zen Hae, pengamat seni rupa Hendro Wiyanto, penulis dan pengamat seni pertunjukan Bambang Bujono, serta pengamat musik David Tarigan.
Karya Nuarta di atas menjadi salah satu pertimbangan kami saat menentukan pilihan karya seni rupa. Untuk bidang seni rupa, kami memperluas pengamatan, bukan hanya karya dalam pameran di ruang tertutup, tapi juga yang disajikan di ruang terbuka. Kami, misalnya, pada 2014 memenangkan instalasi seni bawah laut Teguh Ostenrik, Domus Sepiae, berbentuk ubur-ubur yang dipasang di dasar laut Pantai Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Teguh adalah perupa yang memiliki perhatian terhadap ekosistem laut. Instalasi ini dia buat untuk mengonservasi terumbu karang. Adalah menarik, pada November 2018, Teguh membuat instalasi serupa di bawah laut perairan Pulau Bangka. Kali ini dia memberi judul Domus Hippocampi. Karya ini berbentuk rumah kuda laut.

Patung Garuda Wisnu Kencana di kawasan GWK Cultural Park, Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, 2018. [TEMPO/STR/Johannes P. Christo]
Selanjutnya karya yang membetot perhatian kami adalah pameran instalasi buatan pematung senior Sunaryo berjudul Lawangkala. Sunaryo membuat sebuah lorong dari bambu. Pengunjung bisa memasuki terowongan bambu dan merasakan sensasi kenaturalan. Pameran lain yang kami perhitungkan adalah pameran instalasi rajut benang karya perupa muda Mulyana bertajuk “Multiple Hands”. Pameran ini juga menampilkan obyek cukup besar. Obyek-obyek ini menempati semua ruang pameran di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, pada 3-26 Agustus 2018. Pameran melibatkan puluhan orang yang tergabung dalam Konco Mogus. Ini kelompok perajut ibu-ibu di Yogyakarta yang dibentuk Mulyana untuk mengerjakan proyek-proyeknya yang berbasis rajut benang.
Setelah melalui diskusi cukup panjang, kami akhirnya memutuskan instalasi rajut benang karya Mulyana dalam pameran “Multiple Hands” sebagai karya seni rupa terbaik pilihan Tempo 2018. Alasan utamanya: semua obyek dibuat dengan medium yang jarang digunakan perupa, yaitu benang. Mulyana juga melibatkan puluhan perajut ibu-ibu rumahan—yang sering diabaikan dalam seni rupa kontemporer karena dianggap keterampilan mereka sebatas kategori craft alias kerajinan. Dengan medium seni rajut dengan bantuan ibu-ibu itu, Mulyana menciptakan karakter sosok monster gurita unik yang diberi nama Mogus. Mogus dibuat dengan teknik pompom—menggulung benang pada jari atau dengan benda tertentu membentuk bola.
Awalnya, pada 2012, Mulyana menciptakan “Mogus World I” di Ruang Gerilya, Bandung. Setahun kemudian, ia berpameran “Mogus World II” di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta. Kreativitas Mulyana, menurut kami, memuncak pada pameran tunggal 2018, “Mogus World III”, yang dilaksanakan di Selasar Sunaryo itu. Bukan hanya sosok Mogus yang diciptakan. Sebuah lanskap imajinatif dunia bawah laut juga hadir di sana. Melalui pameran ini, Mulyana merayakan keberagaman rupa dan sensasi warna-warni benang. “Mulyana berupaya melampaui stereotipe seni rupa dekoratif dan membuka jalan baru bagi kepekaan tangan di sekitar kita,” ujar Hendro Wiyanto.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk karya sastra, kami memilih karya prosa dan puisi terbaik. Dari puluhan karya prosa, kami memilih enam nomine prosa, yakni Kura-kura Berjanggut (Azhari Aiyub), Menolak Ayah (Ashadi Siregar), Ular Tangga (Anindita S. Thayf), Buku Panduan Matematika Terapan (Triskaidekaman), Buku Jingga (Nirwan Dewanto), dan Aroma Karsa (Dewi Lestari). Dari enam karya itu, kami kemudian menyaringnya menjadi tiga kandidat: Kura-kura Berjanggut, Menolak Ayah, dan Buku Jingga.
Perdebatan cukup alot terjadi saat menentukan apakah novel Azhari, Kura-kura Berjanggut, atau novel Nirwan, Buku Jingga, sebagai buku prosa terbaik. Dari sisi fisik, kedua karya ini kontras. Novel Azhari sangat tebal, 960 halaman. Sedangkan novel Nirwan tipis, 104 halaman. Deskripsi Azhari memukau. Bagian pertama novelnya berlatar Aceh sekitar abad ke-16. Azhari banyak menggunakan data sejarah pergolakan politik Aceh dan Malaka, tapi cara mengolah data itu tak membuat novelnya jatuh sebagai sebuah roman sejarah biasa. Kura-kura Berjanggut menjadi fiksi yang sangat imajinatif dan tak terduga. Skandal seks, rencana kudeta, pembunuhan, dan sindikat dagang yang dilakukan para pangeran, bajak laut, sampai budak yang melibatkan persekongkolan orang dari berbagai bangsa diolah tingkap-meningkap tapi lancar oleh Azhari.

Pementasan teater Lear di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 2018. Dokumentasi Dewan Kesenian Jakarta.
Akan halnya karya Nirwan Dewanto bermain dengan lapis-lapis. Karya prosa Nirwan menceritakan kehidupan sehari-hari menggunakan alegori dunia pewayangan. Sudah sangat banyak sebetulnya karya sastra yang menampilkan tokoh pewayangan. Tindakan karakter wayang ini kerap digunakan sebagai metafora bagi problem kehidupan aktual. Namun Nirwan melihat selama ini novel atau cerita pendek demikian masih berkutat pada isu moralitas. Belum ada teknik penarasian yang radikal. Paling banter hanya menjungkirbalikkan karakter para tokoh. “Saya tidak mau ke situ. Saya mengosongkan isi, semua tokoh bergerak di wilayah abu-abu, semua bersifat dekonstruktif,” katanya. Nirwan mengaku mengagumi seni rupa bayang-bayang yang disajikan oleh pertunjukan wayang kulit. Hal itu memicu keinginannya untuk menerjemahkan seni rupa bayang-bayang tersebut dalam bentuk sastra. “Itu sebabnya cara penceritaan saya berbentuk bayang-bayang, bergerak di antara prosa dan puisi, di antara yang nyata dan yang maya, di antara yang gelap dan yang terang,” ujarnya.
Setelah berdebat cukup liat, kami akhirnya bersepakat memilih novel Buku Jingga sebagai karya sastra bidang prosa terbaik pilihan Tempo 2018. “Novel Azhari kurang diedit. Ada beberapa bagian yang bertele-tele. Bila dihilangkan, pasti bisa membuat novelnya utuh. Ia seperti ingin memasukkan apa saja,” kata Zen Hae. Sedangkan Seno Gumira Ajidarma melihat dalam novel Azhari ada beberapa bagian yang deskripsi sejarahnya masih sengaja seperti mencari efek. Sedangkan kekuatan novel Buku Jingga Nirwan, menurut Seno, adalah eksplorasinya terhadap bahasa simbolis. “Novel Nirwan itu antara esai dan prosa. Ia melakukan eksplorasi bentuk dan bahasa. Bisa dibilang ini esai yang puitik. Kalimat-kalimatnya matang, padat, dan tak ada yang mubazir,” ujar Seno. Adapun Zen melihat kekuatan karya Nirwan terletak pada permainan sudut pandang penceritaan. Pada bab pertama, Nirwan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pada bab kedua, Nirwan mengubah sudut pandang ceritanya menjadi sudut pandang orang pertama semacam monolog interior.
Untuk bidang puisi, ada tiga kumpulan puisi yang menjadi nomine pilihan kami: Membaca Lambang (Acep Zamzam Noor), Batu Ibu (Warih Wisatsana), dan Rawi Tanah Bakarti (Kiki Sulistyo). Boleh dibilang, ketiga buku kumpulan puisi itu sama-sama berangkat dari hasil pengembaraan penyairnya ke sebuah tempat. Namun kami menilai, dalam Rawi Tanah Bakarti, Kiki Sulistyo menyajikan sebuah kedalaman pengembaraan yang lain—yang tidak sekadar seperti pelancong dalam menangkap suasana.
Kiki semula tinggal di Kota Mataram. Dia kemudian pindah ke sebuah dusun kecil di Desa Ubung, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, empat tahun lalu. Di dusun itu, bahasa Indonesia ibarat bahasa asing. Tidak ada seorang pun yang memakainya dalam komunikasi verbal sehari-hari. Bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa Sasak. Namun bahasa Sasak di desa itu sama sekali berbeda dengan bahasa Sasak yang dikenal Kiki di Mataram sejak kecil. “Hal itu membuat saya sulit berkomunikasi di sana,” ucapnya. Namun masalah ini justru membuat Kiki lebih banyak mendengar, termasuk cara bicara penduduk setempat. Ia merasa bahasa Sasak di dusun itu disampaikan dengan cara dilontarkan. Tak ada orang di sana yang berbicara dengan volume kecil. Ruang privat individu pun nyaris tak dikenal. Di sana, orang senang berbagi, dari makanan hingga cerita. Situasi itu memunculkan imaji dalam diri Kiki, baik tentang sejarah, mitologi, ritus, maupun sistem sosial di dusun tersebut.
Terkadang, saat menulis sebuah puisi, Kiki dihadapkan pada pilihan tetap mempertahankan arti tapi mengorbankan bunyi atau tetap mempertahankan bunyi tapi mengorbankan arti. Ia berprinsip tidak mengorbankan keduanya. “Itulah yang berat, mempertahankan arti ataupun bunyi. Jadi akan saya cari sampai ketemu sehingga kedua hal itu tetap seimbang,” ujar pendiri Komunitas Akarpohon ini. Dalam pandangan Zen Hae, Kiki mampu menampilkan semacam realisme magis dari dusun itu, seperti ritual perdukunan dan mitologi tenun dengan keterampilan bahasa yang terus mencari kemungkinan pengucapan segar serta impresi bunyi. “Kita bisa merasakan penyairnya yang berupaya merebut bahasa sehari-hari menjadi bahasa dia sendiri,” tutur Zen. Selain itu, Zen melihat, sebagai sebuah kumpulan puisi, buku ini utuh—dari awal sampai akhir menggali hal-ihwal Bakarti.

Karya Sunaryo dalam pameran tunggal berjudul “Lawangkala” di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 2018. TEMPO/STR/Prima Mulia
Adapun untuk seni pertunjukan, kami berpendapat tidak banyak pentas seni yang menonjol, baik dari teater maupun dunia tari, pada 2018. Dari puluhan pentas selama 2018, pilihan kami mengerucut pada dua kandidat: pementasan teater Lear oleh Komunitas Berkat Yakin, Lampung, dalam Pekan Teater Nasional yang berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta; dan Sakyamuni itu Saja (Perlu Mati) karya Cokorda Sawitri dalam Borobudur Writers & Cultural Festival di kompleks Candi Borobudur, Magelang, November lalu.
Komunitas Berkat Yakin menyuguhkan Lear versi penulis Jepang, Rio Kishida. Pendekatan penyutradaraan yang dilakukan Ari Pahala Hutabarat, sutradara Komunitas Berkat Yakin, menyegarkan. Ia secara berani menyuguhkan pengade-ganan dengan prinsip kolase. Dari segi musik, misalnya. Dari adegan satu ke adegan yang lain, ia membungkusnya dengan lagu-lagu yang sesungguhnya memiliki karakter berbeda, tapi terasa cocok dan tak bertabrakan. Pada awal pertunjukan, misalnya, pementasan ini mengentak dengan lagu Paint It Black milik The Rolling Stones. Selanjutnya Gregorian Handel, Ave Maria, sampai kemudian, di ujung tragedi, suara penyanyi folk Amerika Serikat, Johnny Cash, mengiringi kematian Lear. Secara dramaturgi, ia juga sering tiba-tiba menyusupkan elemen tari dalam adegan. Unsur tari yang diambil dari khazanah kebertubuhan Sumatera. Koreografi tari ini kadang seperti masuk menusuk, mengangkat adegan, kadang membelokkan adegan untuk berganti ke suasana lain. Cara penyutradaraan demikian cerdas dan jarang dilakukan. Yang mungkin kurang dari pengamatan para juri adalah proporsi antara tari dan adegan serta keaktoran yang tidak merata. Suasana yang ada di panggung lebih terbentuk oleh unsur musik dan tari daripada dialektika dan kekuatan aktor-aktornya. Setelah beradu argumentasi cukup panjang, kami akhirnya bersepakat memilih pertunjukan Sakyamuni itu Saja (Perlu Mati) sebagai seni pertunjukan Tempo 2018.
Cokorda Sawitri menyuguhkan pentas yang berbeda dari pertunjukan tari dan teater kita masa kini yang cenderung riuh, menyisipkan gerak tari atau adegan yang gaduh. Lewat Sakyamuni itu Saja (Perlu Mati), Cok—sapaan akrab Cokorda—mengangkat pentas yang bersahaja tanpa banyak bunga-bunga, tapi subtil. Dia menggabungkan puisi, mantra, dan gerak. Sebuah puisi dibacakan, diiringi visualisasi gerak, kemudian disisipi lantunan mantra suci yang diambil dari komunitas Siwa-Buddha di Bali. Ketiga unsur ini berpadu dengan utuh, sama sekali bukan tempelan. Cok menampilkan bahasa panggung yang hemat tapi sublim. Gerak koreografinya minimal, karena itu terasa sederhana. “Justru dalam kesederhanaan itu ia menyapa dengan datar, tapi meninggalkan jejak yang mendalam,” kata Bambang Bujono.
Di bidang industri rekaman musik, kami mengamati tahun 2018 diwarnai oleh banyaknya album hip-hop/rap. Di antaranya, album Swagton Nirojim (Krowbar), Waktu Bicara (Laze), Demi Masa (Morgue Vanguard x Doyz), dan Monkshood (BAP.). Dengan balutan musik hip-hop/rap yang mengentak, album-album itu berisi lirik yang mengkritik dan menggelitik tentang berbagai hal, dari kehidupan sosial -masyarakat urban di kota-kota besar di Indonesia hingga situasi politik saat ini.

Domus Sepiae karya Teguh Osterik di dasar laut Pantai Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2104. Dokumentasi Teguh Ostenrik
Selain merilis album hip-hop/rap, industri rekaman tahun 2018 menelurkan puluhan album folk, pop, jazz, blues, hingga rock. Kami kemudian menyaringnya menjadi sepuluh album. Dari sepuluh album itu, kami memilih satu untuk dinobatkan sebagai album terbaik pilihan Tempo 2018. Pilihan kami mengerucut pada dua kandidat: album Sujud (Senyawa) dan La Marupè (Theory of Discoustic).
Boleh dibilang, kedua album itu memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga kami cukup kesulitan menentukan pilihan. Akhirnya kami memilih album Theory of Discoustic, La Marupè. Theory of Discoustic adalah kelompok musik folk asal Makassar yang tertarik menggali khazanah kebudayaan Bugis-Makassar. Salah satu kekuatan La Marupè terletak pada lirik-lirik lagunya yang dibangun dari dunia cerita rakyat -(folklore) dan adat istiadat Bugis-Makassar. “Mereka menyuguhkan delapan komposisi pembacaan kembali folklore Bugis-Makassar dan sejarah Nusantara dalam wujud ekspresi yang tertakar dengan baik,” ujar David Tarigan.
David menambahkan, Theory of Discoustic meramu cerita-cerita rakyat yang digali melalui penelitian sekitar dua tahun. Mereka menggunakan instrumen band tanpa alat musik tradisional. Theory of Discoustic tidak berusaha menjadi grup musik yang tampil dengan kosmetik alat musik tradisional sebagaimana banyak dilakukan kelompok lain. Mereka tidak menggunakan instrumen-instrumen musik tradisi, yang memang tidak mereka kuasai. “Sebagai kelompok folk, mereka berusaha wajar. Tapi, dengan formulasi seperti itu, mereka berhasil mencapai bentuk ramuan yang pas dan eksekusinya tepat sasaran,” kata David. Poin-poin itulah yang membuat kami bersepakat menobatkan La Marupè sebagai album terbaik pilihan Tempo 2018.
Sumber: majalah.tempo.co